Pendidikan Harus Inklusif
Afthal Nurdiansyah Putra
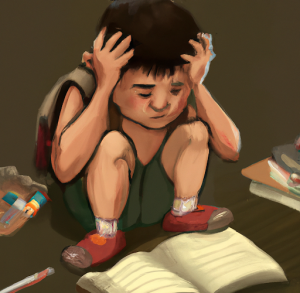
Dall-E
Pendidikan adalah proses pemberian dan penerimaan pengetahuan; keterampilan; nilai-nilai; dan etika yang dilakukan melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Salah satu tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Praktik pendidikan bisa dilakukan dalam berbagai tempat, seperti di sekolah, universitas, lembaga pelatihan, dan lingkungan nonformal. Di beberapa negara, sistem pendidikan diatur oleh pemerintah dan memiliki kurikulum yang ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat, diharapkan, menerima pengetahuan yang penting dan relevan. Namun, dalam praktiknya, akses kepada pendidikan sering kali tidak inklusif. Beberapa golongan masyarakat, seperti masyarakat golongan menengah ke bawah, masyarakat yang difabel, dan lain lain tidak jarang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, bahkan nihil.
Masyarakat menengah ke bawah sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan. Beberapa kesulitannya adalah tinggal di daerah yang terpencil, infrastruktur pendidikan yang terbatas, atau jarak yang jauh dari sekolah (Hardiasanti & Trihantoyo, 2021). Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam mengakses pendidikan. Di perguruan tinggi, misalnya, biaya pendidikan menjadi pertimbangan bagi golongan miskin. Uang Kuliah Tunggal (UKT), uang pangkal, Sumbangan Sukarela Pengembangan Institusi (SSPI), dan lain lain menjadi beban yang berat bagi keluarga miskin. Hal ini tentu menghambat aksesibilitas kepada pendidikan bagi kaum miskin. Dengan problem seperti ini, inklusivitas pendidikan tidak dapat terpenuhi karena pendidikan dianggap hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya. Masalah aksesibilitas pendidikan juga bisa berkaitan dengan jarak. Pendidikan yang berkualitas mungkin berada di daerah yang jauh dari tempat tinggal keluarga miskin. Jika transportasi tidak terjangkau atau tidak tersedia, anak-anak mungkin kesulitan untuk mencapai sekolah secara teratur dan mengakses pendidikan yang diperlukan.
Tak hanya itu—mengingat pendidikan yang inklusif berarti akses terhadap pendidikan harus bisa oleh semua golongan—sistem pendidikan juga harus mengakomodasikan akses bagi kaum difabel. Banyak institusi pendidikan, terutama yang telah ada sejak lama, tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk akses fisik kaum difabel. Misalnya, bangunan yang tidak memiliki rampa atau lift untuk kursi roda, tangga yang curam atau sempit, dan toilet yang tidak ramah difabel. Hal ini menyulitkan kaum difabel untuk masuk dan berpartisipasi dalam proses pendidikan. Kurikulum dan materi pembelajaran sering kali tidak disesuaikan dengan kebutuhan kaum difabel. Materi yang disajikan mungkin tidak aksesibel bagi siswa dengan berbagai jenis disabilitas, seperti siswa dengan disabilitas penglihatan (tunanetra) yang tidak memiliki buku dengan huruf braille, siswa dengan disabilitas pendengaran (tuna rungu) yang tidak memiliki akses terhadap terjemahan bahasa isyarat, atau siswa dengan disabilitas intelektual yang tidak memiliki pendekatan pembelajaran yang sesuai. Lebih lanjut, stigma sosial dan diskriminasi terhadap kaum difabel juga dapat menyebabkan sulitnya akses terhadap pendidikan. Kaum difabel sering mengalami perlakuan diskriminatif, pelecehan, atau pengucilan di lingkungan pendidikan. Hal ini tidak hanya menghalangi akses mereka ke pendidikan, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan perkembangan mereka secara keseluruhan. Melihat dari masalah tersebut, pendidikan yang inklusif ternyata tidak hanya berhenti pada aksesibilitas, tetapi juga harus menjadi ruang aman bagi semua peserta didik di dalamnya.
Pendidikan sebagai ruang aman, sejatinya, memberikan kebebasan kepada individu untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, dan keyakinan mereka tanpa takut dicemooh atau dihukum. Hal Ini mencakup kebebasan berbicara, berpendapat, dan berpartisipasi dalam diskusi terbuka. Hal ini mendorong individu untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide baru, berani untuk bertanya, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya, beberapa instansi pendidikan belum bisa menjadi ruang aman. Kasus-kasus seperti perundungan, diskriminasi terhadap minoritas, pelecehan dan kekerasan seksual, dan lainnya masih terus menjadi hal yang eksis di ruang pendidikan (Bukhari, 2022). Implikasinya, individu-individu yang “terancam” tersebut mengalami kesulitan untuk mengekspresikan gagasannya, lebih jauh lagi, tidak bisa mengeksplorasi potensi dalam dirinya.
Permasalahan inklusivitas pendidikan ternyata sudah ada sejak dahulu. Tidak sedikit filsuf yang mengkritik masalah pendidikan yang tidak inklusif ini. Salah satunya adalah Ivan Illich, yang mengkritik bahwa latar belakang individu yang ingin bersekolah adalah karena ada suatu “rahasia” tentang aspek dalam hidup ini, kualitas kehidupan tergantung pada upaya untuk membongkar “rahasia” itu, dan hanya guru yang secara tepat membongkar “rahasia-rahasia” itu (Illich, 2002). Dengan kata lain, pendidikan hanya bisa dilakukan di lembaga sekolah. Namun—seperti yang sudah dibahas sebelumnya—lembaga sekolah tidak bisa diakses oleh semua golongan individu. Oleh karena itu, Illich berpendapat, kewajiban bersekolah akan membagi masyarakat dalam kutub-kutub yang bertentangan. Illich mengusulkan konsep deschooling, yang ditulis dalam Deschooling Society, yang berupaya menuntaskan masalah pendidikan ini. Deschooling, menurut Illich, melibatkan pembebasan pendidikan dari kendali institusi sekolah dan memberikan kekuasaan pendidikan kembali kepada individu, keluarga, dan komunitas. Ia berpendapat bahwa pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama yang dijalankan oleh masyarakat itu sendiri, di luar batasan formal institusi sekolah. Illich mempromosikan pendekatan pendidikan yang lebih terdesentralisasi, yang membuat individu dapat belajar dari sumber daya lokal, seperti orang yang memiliki keahlian khusus, perpustakaan, komunitas, atau melalui hubungan pribadi.
Di sisi lain, Miranda Fricker memiliki pendekatan yang lain untuk menyikapi permasalahan inklusivitas pendidikan. Pemikiran Fricker didasari pada pernyataan bahwa, gagasan dan pengetahuan berperan penting dalam pembuatan makna yang inklusif sehingga siapapun yang memiliki akses ke ruang epistemik ini kemudian menjadi problem keadilan (Walker, 2019). Menurut Fricker, ada ketidakadilan yang terjadi dalam lingkup pengetahuan. Fricker berpendapat bahwa ada ketidakadilan struktural dalam cara kita memperoleh, mempertahankan, dan menghargai pengetahuan, yang secara khusus mempengaruhi kelompok-kelompok yang secara historis telah menghadapi penindasan dan marginalisasi (Pohlhaus, 2012). Ketidakadilan epistemik tidak hanya menghalangi aliran pengetahuan, tetapi juga aliran bukti, keraguan, ide kritis, dan masukan epistemik lainnya (Hull, 2015). Fricker menjelaskan kemampuan kontribusi epistemik diambil sebagai kebebasan pendidikan yang merupakan hal inti di semua tingkat pendidikan formal. Selain itu, kemampuan tersebut akan memenuhi salah satu kebutuhan dasar kita yang paling manusiawi. Hal ini membuat Fricker menaruh perhatian pada sistem egaliter karena kebutuhan manusia kita yang spesifik untuk menggunakan penalaran teoretis dalam membuat makna dan menjalankan hak dan pilihan kita. Proses mengesampingkan seorang siswa, katakanlah karena kebangsaan, etnis, bahasa atau prasangka gender, adalah proses menghambat pertumbuhan epistemik dan penyalahan mereka “dalam kapasitas mereka sebagai subjek epistemik” (Fricker 2007).
Setelah berkaca dari masalah inklusivitas pendidikan dan sudut pandang beberapa filsuf di atas, pendidikan yang inklusif adalah prinsip yang sangat penting untuk diadopsi dalam sistem pendidikan. Melalui pendidikan yang inklusif, hak asasi manusia diakui, pendidikan untuk semua dapat diwujudkan, toleransi ditingkatkan, dan potensi individu diberdayakan. Pendidikan yang inklusif tidak hanya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil, tetapi juga mempersiapkan generasi masa depan yang siap menghadapi kompleksitas dunia yang semakin terhubung dan beragam. Oleh karena itu, upaya untuk membangun sistem pendidikan inklusif harus terus diperjuangkan.
Daftar Pustaka
Bukhari, I. (2022). SOP Untuk Membangun Sekolah Anti Bullying [YouTube]. Abaihsan Channel. https://www.youtube.com/watch?v=MrpRG83pC7s
Fricker, M. (2007). Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford University Press.
Hardiasanti, M., & Trihantoyo, S. (2021). Implementasi Wajib Belajar di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal. Inspirasi Manajemen Pendidikan, 9(5). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/43255
Hull, G. (2015). The Equal Society: Essays on Equality in Theory and Practice. Lexington Books.
Illich, I. (2002). Deschooling Society. Marion Boyars.
Pohlhaus, G. (2012). Relational Knowing and Epistemic Injustice: Toward a Theory of “Willful Hermeneutical Ignorance”. Hypatia, 27(4), 715-735. https://www.jstor.org/stable/23352291
Walker, M. (2019). Why Epistemic Justice Matters in and for Education. Asia Pacific Education Review, 20, 161-170. https://doi.org/10.1007/s12564-019-09601-4

PPSMB DIALEKTIKA 2023
Jl. Olahraga, Karang Malang, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281